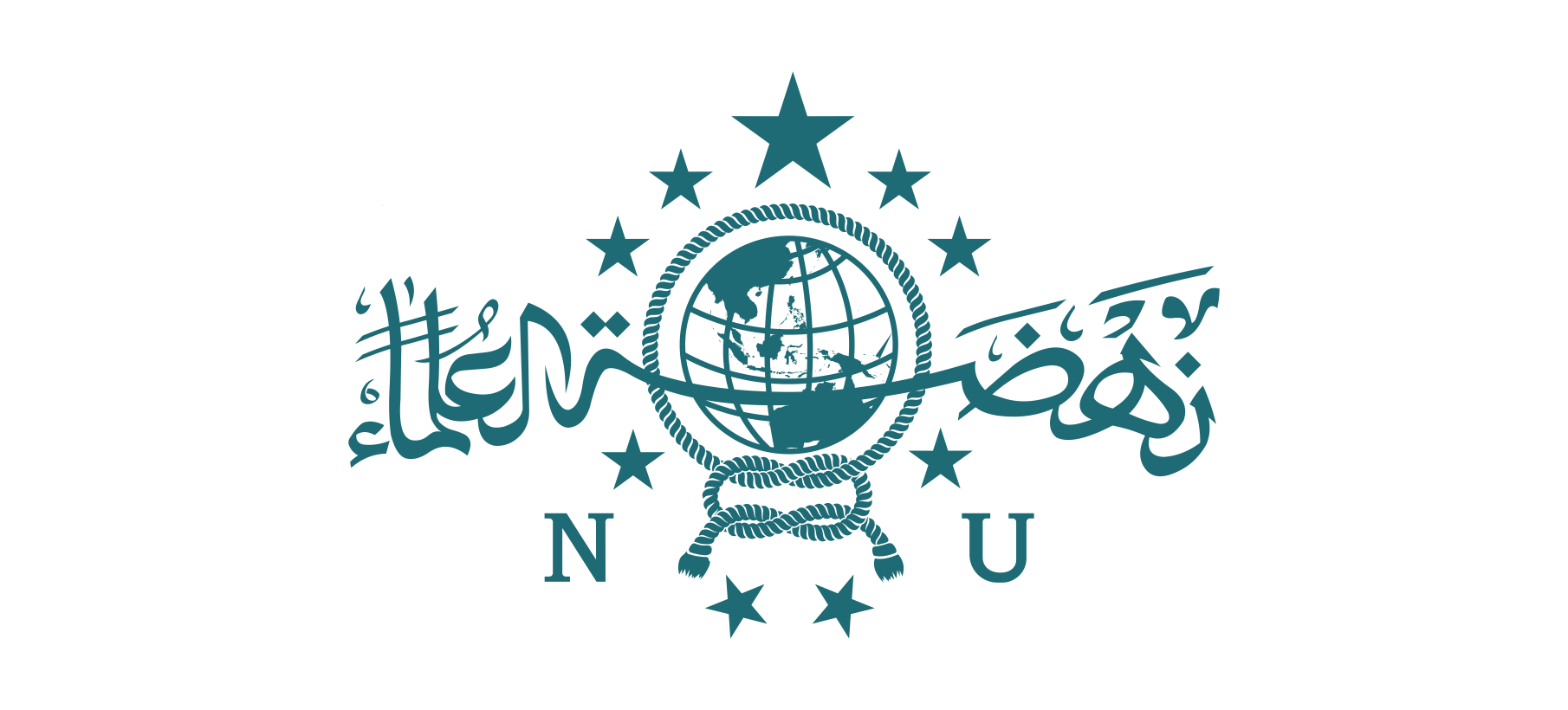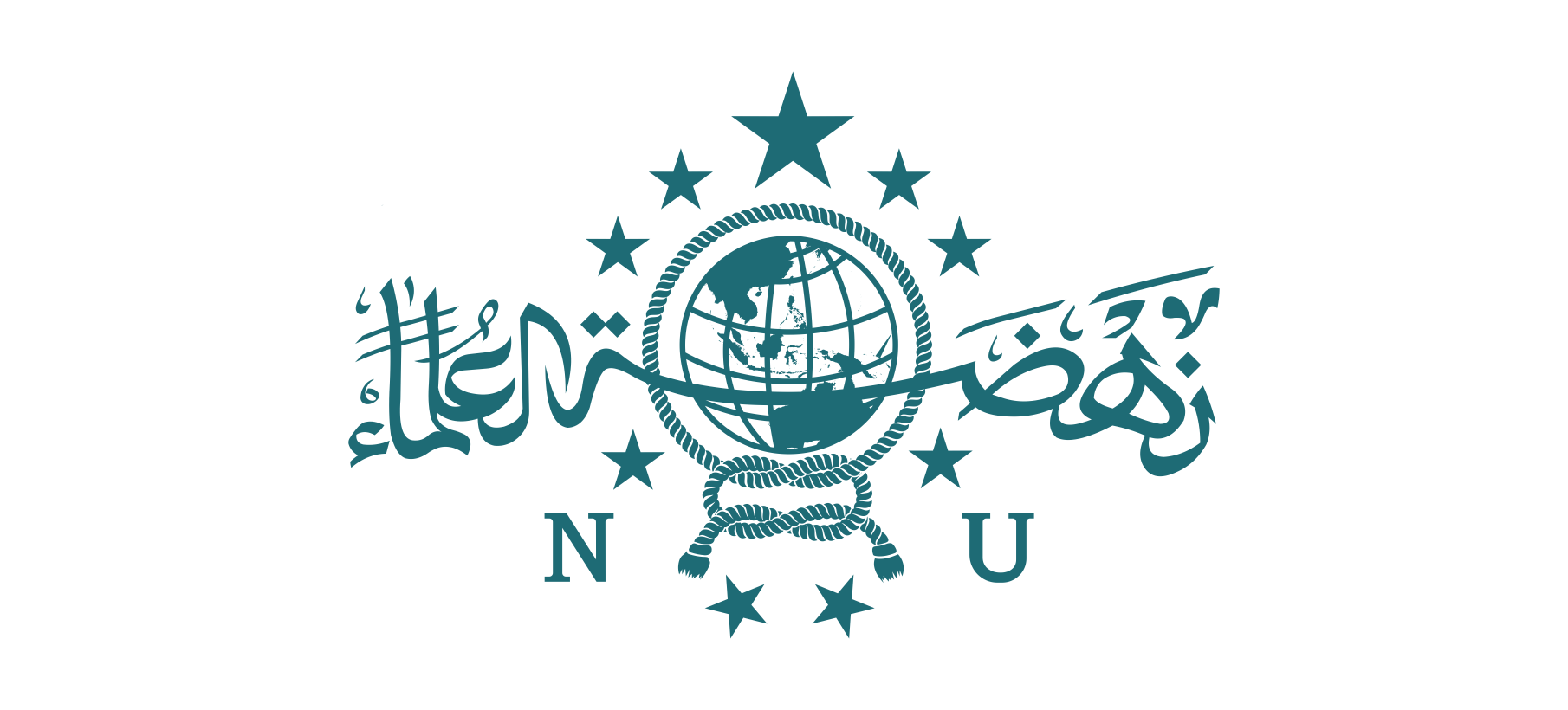Oleh: Muhammad Zuhdi
Di tengah derasnya arus pragmatisme dan individualisme yang menenggelamkan makna pengabdian, berkhidmat di Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) justru hadir sebagai oase spiritual dan jawaban atas kekeringan nilai dalam kehidupan kontemporer. Bagi sebagian orang, berkhidmat dalam organisasi keagamaan seperti NU dianggap sebagai sesuatu yang membosankan, menguras tenaga, bahkan terkesan sia-sia. Namun, bagi yang memahami esensinya, berkhidmat bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan kebutuhan ruhani yang mendalam.
Dalam dimensi eksistensial, manusia bukan hanya makhluk yang bekerja untuk hidup, tetapi juga hidup untuk memberi makna. Maka, berkhidmat di NU menjadi medium sublimasi diri—tempat di mana jiwa yang letih oleh rutinitas duniawi menemukan ketenangan, kepercayaan diri, dan kekuatan batin. Pengabdian itu sendiri adalah bentuk tertinggi dari aktualisasi spiritual yang menjadikan seseorang tak sekadar hidup, tetapi hidup secara bermartabat.
Lebih dari itu, NU bukan organisasi biasa. Ia adalah jam’iyah yang lahir dari rahim para wali, para ulama yang telah mencapai maqam hakikat dalam maqashid kehidupan. Didirikan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dan para ulama sepuh lainnya, NU telah terbukti menjadi benteng moral dan penjaga akidah Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah yang kokoh selama lebih dari seabad.
Dalam sejarah panjangnya, berbagai ancaman dan rongrongan pernah mencoba meruntuhkan NU—baik dari eksternal maupun internal. Namun, semua itu gugur dengan sendirinya, seolah tak kuasa menghadapi daya spiritual yang menyelimuti jam’iyah ini. Dalam bahasa tasawuf, ini bukan semata kekuatan struktural, tetapi “karomah jam’iyah”—berkah yang lahir dari ikhlasnya pendiri dan tulusnya para pejuang NU dari generasi ke generasi.
Realitas membuktikan, banyak pengkhidmat NU yang hidupnya tampak sederhana, namun hatinya lapang, jiwanya tenang, dan keluarganya diberkahi. Mereka bukan orang yang mengejar dunia, tetapi dunia yang datang kepada mereka. Fenomena ini menggambarkan makna filosofis dari “barokah”, yang tak selalu linier dengan logika ekonomi, tapi nyata dalam kualitas hidup.
Sebagai generasi muda NU, kita tidak cukup hanya hadir sebagai pengikut. Kita harus menjadi pelaku sejarah, bukan sekadar pembaca sejarah. Kita harus hadir sebagai pemikir strategis dan pelaksana gagasan—sebagai eksekutor program yang progresif dan solutif. Kita tak boleh hanya mengurus organisasi, tapi juga mengurusi umat. Kita tidak boleh hanya mencintai NU, tapi juga memperjuangkannya dalam tataran praksis.
NU adalah wasilah peradaban. Ia bukan sekadar institusi, melainkan gerakan nilai, budaya, dan spiritualitas. Maka, menjadi kader NU adalah menjadi penjaga nilai, pewaris ajaran, dan pemikul amanat. Kita wajib menjaga, merawat, dan mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdliyah sebagai fondasi kebangsaan dan kemanusiaan.
Kita yakini bersama, bahwa dengan berkhidmat secara total dalam jam’iyah ini, kita sedang menapaki jalan para wali. Jalan yang tak selalu mudah, tapi penuh berkah. Jalan yang mungkin sunyi, tapi diridhoi. Jalan yang akan mengantarkan kita—insya Allah—berkumpul bersama KH. Hasyim Asy’ari dan para pendiri NU di yaumil akhir, sebagai santri yang istiqamah dalam khidmat.
Informasi Penulis:
Muhamamad Zuhdi, merupakan Ketua Pimpinan Anak Cabang Pencak Silat Nahdlatul Ulama’ Pagar Nusa Kecamatan Gambiran.
Redaksi:
Opini ini merupakan bentuk refleksi kebatinan atas makna pengabdian dalam jam’iyah Nahdlatul Ulama. Pandangan ini tidak mewakili institusi tertentu, namun menjadi narasi yang lahir dari keyakinan dan pengalaman batin sebagai bagian dari generasi muda NU yang peduli akan keberlangsungan nilai dan peradaban.